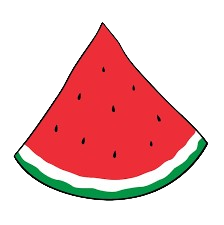Takdir yang Sama

Ganjil. Suara tukang gejrot itu terdengar ganjil di malam hari. Setahuku, di sini, tukang tahu gejrot biasa berjualan siang atau sore hari. Aku tidak tahu kalau di tempat lain.
Karena penasaran, suatu malam, aku pergi keluar untuk melihatnya. Tetapi aku tidak menemukan ada tukang gejrot di sepanjang jalan di depan rumahku. Ia pastinya sudah berbelok ke kanan di pertigaan jalan atau di perempatan berikutnya.
Malam berikutnya, ketika samar-samar kudengar suara panggilan tukang tahu gejrot, aku segera keluar. Aku menengok kanan dan kiri. Tapi lagi-lagi aku tidak menemukannya. Aku berdiri di pintu pagar sejenak, berpikir bahwa tukang gejrot itu sama dengan tukang gejrot yang pernah mangkal di pertigaan SMA antara jam satu dan jam tiga siang.
Meskipun sudah lama tidak melihatnya, aku masih ingat penjualnya. Ia seorang lelaki tua, usianya tidak kurang dari enam puluh, sebagian rambutnya putih, hidungnya pesek, matanya sipit, badannya kecil dan bungkuk. Ia selalu memakai kemeja batik yang kebesaran, celana panjang hitam digulung sebetis dan sandal jepit butut.
Tidak banyak yang membeli tahu gejrotnya. Bukan karena orang-orang tidak menyukai tahu gejrot, melainkan karena gerobaknya yang butut dan kotor, dan penampilan tukangnya yang kusam. Aku pernah membelinya satu kali. Untuk harga lima ribu rupiah, tahu gejrotnya lumayan banyak. Rasanya mirip seperti tahu gejrot lainnya, hanya kuahnya lebih butek, tahunya agak pahit, dan ada seekor lalat hijau mati di dalamnya!
Sungguh, itu jadi pengalaman terburuk selama aku makan tahu gejrot. Seingatku, saat itu aku marah besar dan berniat menuntutnya untuk bertanggung jawab; ia akan membuatkanku tahu gejrot yang baru atau mengembalikan uangku. Namun, begitu melihat wajah keriputnya dan mata sendunya yang seakan-akan ada sesuatu yang memberati pikirannya, aku malahan jadi merasa kasihan. Aku tidak jadi minta ganti rugi dan memilih membuang lalat hijau itu. Aku menghabiskan tahu gejrotku. Kupikir, aku tidak akan mati karena lalat. Paling parah aku hanya akan sakit perut, dan itu pun tidak perlu pergi ke dokter.
“Tinggal di mana, Beh?” tanyaku setelah membayar tahu gejrotnya. Setelah amarahku reda.
“Ngontrak di Kranji,” jawabnya, suaranya serak. Wajahnya tampak ketus.
Jarak Kranji dari sini kira-kira tiga kilometer. Untuk orang setua dirinya, mendorong gerobak dari Kranji ke tempat ini lalu lanjut berkeliling dan berjalan pulang pasti sangat menyiksanya.
“Bikin sendiri?”
“Ikut orang.”
Sama seperti tahu gejrotnya yang tidak pernah kubeli lagi, aku bicara dengannya sekali itu saja. Lusanya ia tidak lagi mangkal sana. Mungkin ia tahu tempat itu tidak menguntungkan. Ia memang masih berjualan keliling komplek, tetapi itu hanya berlangsung selama dua atau tiga hari, setelah itu ia tidak pernah terlihat lagi.
Aku tidak tahu tepatnya sudah berapa lama ia menghilang, yang kutahu kemunculannya di malam hari jadi bahan obrolan orang-orang. Pertama, baru kali ini ada tukang tahu gejrot yang jualan malam. Kedua, suara panggilannya yang pakai pengeras suara dan lonceng kecil itu sangat berisik dan mengganggu. Ketiga, bocah-bocah komplek menyangkanya hantu.
Tentu saja ia bukan hantu. Aku menemukannya sedang mangkal di dekat lapangan basket pada Sabtu malam.
Dugaanku betul, ia tukang gejrot yang sama, yang mangkal di pertigaan SMA, seorang pria enam puluh tahunan berwajah kecil dan berambut putih. Bedanya, gerobaknya sudah berubah jadi lebih bagus dan pembelinya lumayan banyak. Sayangnya, sejak kejadian lalat hijau itu, aku sudah tidak berminat lagi membeli tahu gejrotnya.
Rasa penasaranku terbayar sudah malam itu. Aku tidak perlu lagi bergegas keluar rumah untuk mencari tahu apakah tukang tahu gejrot itu manusia atau hantu.
Aku baru saja melangkah pergi ketika kudengar seseorang memanggilku dari belakang.
“Hei, Bardi!”
Mula-mula aku tidak mengenali sosoknya yang terlindung bayangan rimbunan dedaunan, tetapi aku kenal betul suaranya.
“Surya? Itukah kau?”
Kemudian akhirnya ia menampakkan dirinya dan berjalan menghampiriku. Benarlah, bahwa sosok itu kawan baikku yang bernama Surya.
“Kemana saja kau?”
“Aku tidak pernah pergi dari komplek ini.”
Ia tertawa keras sekali, dan berkata, “Kau baru bangun ya?”
“Sial! Apa maksudmu?”
“Kau ingat aku pernah bilang kita bertemu karena takdir bersama?”
“Ya, aku ingat.”
“Sekarang kita bertemu lagi juga karena takdir yang sama.”
Ucapannya mengingatkanku saat pertama kali kami bertemu. Waktu itu aku sedang bertarung mati-matian melawan tiga begal di tepi tepi jalan yang sepi. Ketiganya membawa parang dan clurit, mengancamku akan membunuhku kalau aku tidak menyerahkan ponsel dan sepeda motorku.
Aku bisa saja menuruti permintaan mereka, tapi aku sedang menghitung tingkat keberhasilanku jika melawan, berteriak minta tolong, atau kabur dengan meninggalkan sepeda motorku. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi aku bisa dibilang bernyali besar dan bisa sedikit bela diri. Jadinya, kuputuskan untuk memilih diam saat mereka terus-terusan mengancamku.
Melihatku tidak merespon, salah seorang dari mereka melayangkan sabetan clurit ke arah lenganku. Aku berhasil menghindari, sehingga yang diserangnya hanya tempat kosong. Tentu saja tindakanku itu membuat mereka semakin bersemangat untuk menghabisiku. Namun, sebelum itu terjadi, aku sudah menarik kunci motor, melompat dari sepeda motorku, dan mundur dua atau tiga langkah.
Aku berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang berani menolongku. Orang-orang hanya melewatiku begitu saja.
Mereka menyerangku lagi, tapi aku berhasil menghindar. Aku mundur beberapa langkah, tapi tidak bisa lebih jauh lagi, karena ada tembok pagar di belakangku. Aku berpikir untuk menyerah saja. Aku mengangkat kedua tanganku, dan berkata,
“Aku menyerah! Aku menyerah!”
Tetapi mereka masih enggan menurunkan senjata. Mungkin mereka mengira aku sedang berpura-pura. Untuk meyakinkan mereka, aku akan mengeluarkan kunci sepeda motorku dari kantong celana, lalu melemparnya kepada mereka.
“Aku menyerah.” Aku memberi tanda supaya mereka menurunkan senjata mereka, dan pelan-pelan aku menurunkan tanganku untuk mengambil kunci dari kantong celanaku. “Lihatlah!” Aku menunjukkan kunci sepeda motorku.
Aku baru akan melempar kunci itu ketika seseorang dengan sepeda motor tiba-tiba muncul dan menabrak jatuh salah satu begal.
Tanpa pikir panjang, aku langsung menyambar parang milik begal yang terlepas, yang selanjutnya kupakai untuk menghabisi begal yang baru bangkit itu, dan menghabisi satu lainnya yang akan menyerang si pengendara motor. Sementara itu, satu begal yang tersisa dihabisi si pengendara sepeda motor dengan clurit.
Pengendara sepeda motor itu bernama Surya. Kami berkenalan di kantor polisi. Dari penampilannya, aku menebak ia dua atau tiga tahun lebih tua dariku. Tetapi aku baru tahu usia sebenarnya yang seumuran denganku, delapan belas tahun, saat polisi meminta keterangan kami. Aku tidak menyesal sudah membunuh mereka mengingat itu bukan salahku, kataku pada polisi. Begitu pun dengan Surya.
“Ini masalah hidup atau mati,” kata Surya bersemangat. “Kita yang mati, atau mereka?”
Kasus yang kualami bukan yang pertama kali terjadi. Aku pernah mendengar berita serupa, dan sangat disayangkan ketika korban begalnya malah yang dipenjara. Kalau memang itu yang akan terjadi pada kami, kami sudah siap dipenjara.
Kami ditahan selama seminggu sebelum akhirnya dibebaskan. Rupanya, desakan orang-orang di sosial media yang membela kami dan berita-berita tentang kami yang tayang selama berhari-hari berhasil membuat polisi berubah pikiran untuk membebaskan kami. Kami bahkan dapat penghargaan dari walikota atas keberanian kami. Kami jadi selebritis selama beberapa minggu; jadi tamu di acara berita dan talk show di TV dan podcast di YouTube. Dalam satu podcast, Surya menyebut pertemuan kami karena takdir yang sama.
Meskipun demikian, sebutan yang sama untuk pertemuan kami malam ini tentu saja tidak tepat mengingat ia sudah cukup lama meninggal. Aku bahkan ikut menyalatkannya, memakamkannya dan datang ke tahlilan pertamanya.
“Kau salah,” kataku. “Kita tidak bertemu malam ini karena takdir yang sama. Sobat, kau sudah lama mati sedangkan aku masih hidup.”
Surya tersenyum memaklumi ketidaktahuanku. Ia juga pernah mengalaminya, katanya, kemudian menjelaskan bahwa, lima hari setelah ia meninggal, aku pergi menyusulnya. Ya, aku mati. Dengan cara yang sama. Diracun. Ia bilang kami berdua mati diracun tukang tahu gejrot yang sama. Tukang gejrot itu ayah dari tiga begal yang kami bunuh.
Tentunya aku tidak begitu saja percaya padanya. Tetapi ia sepertinya tahu keresahanku, karena itu ia melakukan sesuatu untuk kupahami. Ia mengambil batu kerikil dan melemparkannya ke arah gerobak tahu gejrot. Terdengar bunyi benturan keras, membuat tukang gejrot dan dua pembelinya terkejut. Mereka melihat ke arah kami, tetapi mereka tidak tahu kami ada di depan mereka, padahal pada saat itu kami sedang duduk di tepi trotoar di bawah lampu jalan yang terang.
“Cobalah.”
Aku mengikutinya, tetapi aku melemparnya ke arah gerobak tukang siomay di sebelah tukang tahu gejrot. Tukang siomay yang sedang merokok terlonjak kaget. Ia celingak-celinguk mencari-cari siapa yang melempar batu ke gerobaknya. Aku melakukannya sekali lagi.
Aku terdiam sejenak. Sepertinya aku bisa menerima aku bukan lagi manusia hidup, apalagi samar-samar aku mulai ingat masa-masa kritisku saat aku muntah-muntah. Aku terpikir untuk balas dendam kepada tukang tahu gejrot brengsek itu. Aku akan mengambil pisau di atas gerobaknya dan merobek perutnya seperti yang pernah kulakukan pada dua anaknya. Tapi itu hanya pikiran konyol. Lagi pula, kenapa Surya tidak melakukannya lebih dulu?
Aku memandangi langit yang bersih itu, dengan awan-awan putih yang mengelilingi cahaya bulan. Merasakan angin yang bertiup pelan dan dingin. Sejak peristiwa begal itu, aku dan Surya berteman baik. Kami sama-sama tidak berniat lanjut kuliah atau bekerja. Yang kami ingin lakukan menjelajah negeri ini dengan sepeda motor. Surya punya adik perempuan cantik yang setahun atau dua tahun lebih muda dari adikku. Aku sering menggoda Surya bahwa aku akan jadi iparnya. Ia biasanya hanya menjawabnya dengan tertawa kecil, kecuali, seingatku ketika satu kali ia berkata, “Semoga saja.” Namun sayangnya, sebagaimana kautahu, hal itu tidak akan pernah terjadi.
“Ada lalat dalam tahu gejrotku,” kataku.
“Itu menjijikkan.”
“Tapi aku menghabiskannya.”
Kami tertawa. Lalu setelah itu ada keheningan yang lumayan lama sebelum akhirnya Surya berkata,
“Kau tahu, aku sudah menunggumu selama setahun untuk memberitahumu hal ini.”
“Ternyata sudah selama itu. Kalau tahu aku bakalan begini, aku seharusnya tidak usah bangun.”
*
Sekitar jam setengah sepuluh tempat itu berangsur-angsur sepi. Di lapangan bola basket hanya tersisa satu orang yang masih mengasah tembakannya ke dalam keranjang. Gerakannya lincah, lemparan tiga angkanya sempurna. Semuanya masuk ke dalam keranjang. Ia mengambil handuk dari dalam tasnya, mengelap wajah, leher dan lengannya, memandang ke arah kami, minum, dan beristirahat sejenak sebelum pulang. Aku melihatnya tiga atau empat jam lalu di rumah, saat ia bersiap-siap pergi untuk berlatih basket, mengambil sepedanya dan pergi ke rumah temannya. Di usianya yang baru empat belas tahun, ia sudah sangat membanggakan orang tuanya dengan nilai-nilai pelajarannya yang bagus dan menjadi kapten tim bola basket di sekolahnya. Ia adik bungsuku. Aku yang mengajarinya bermain bola basket.
Di tempat lain, beberapa pedagang mulai membereskan gerobak. Sebagian lain masih menunggu pembeli. Hanya tukang nasi goreng yang masih ramai. Tidak jauh dari situ, di samping kantor RW, tukang tahu gejrot sedang menghitung uang di atas kursi kayu. Tahu di dalam kotak kaca gerobak hanya tersisa sedikit, botol-botol air kuahnya hampir kosong. Ia memasukkan uangnya ke dalam tas pinggangnya, menggantung kursi plastiknya di depan gerobak, kemudian pergi meninggalkan tempat itu.
* * *